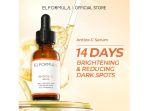Menyelami Zaman Edan dan Ronggowarsito yang Menolak Hegemoni
Cungkup itu berbentuk joglo kayu berukir, terbuka, dengan tirai tipis diikat pada empat tiang penyangga.
Karya sastra Jawa, menurut Fay, sapaan akrab Hilmar Farid, tidak seperti literatur dalam pengertian sastra Eropa. Namun, pihak penjajah memaksakan kodifikasi yang stabil dari filologi yang dasarnya Yunani dan Latin. Yang dipersoalkan adalah originalitas, sumber pasti dari teks.
Sementara, dalam tradisi Jawa, kepastian sumber bukanlah segalanya. Corpus (himpunan) pengetahuan dibentuk melalui tulisan banyak orang dan bersumber pada warisan pengetahuan dari abad ke abad. Seperti proses penulisan Babad Tanah Jawi, sebelum dipotong-potong oleh Meinsma, atas dasar politik kultural-ideologis tentang sastra dan bukan sastra.
Praktik kolonialisasi pengetahuan Barat (penjajah) terhadap Timur (jajahan), yang disebut antara lain oleh Edward Said (1978), tak sulit dirunut. Menurut Fay, siklus apropriasi (mengambil karya lama untuk menyusun karya baru) pengetahuan dimulai akhir abad ke-18. Akhir abad ke-19 mereka mulai merumuskan definisi tentang bahasa dan sastra Jawa. Dengan itu, ilmuwan Belanda, Steward Cohen, menyatakan, pengetahuan Ronggowarsito tentang Jawa Kuno sangat minim.
"Saat itulah pengambilalihan pengetahuan sudah terjadi secara lengkap melalui institusi pendidikan," ungkap Fay.
Pengalaman serupa terjadi di India. Namun, berbeda dengan Tagore yang berusaha merumuskan kebaruan dengan berpijak pada tradisi, Ronggowarsito melawannya dengan kembali pada tradisi dan pengetahuan yang dimiliki. Kegelisahannya diekspresikan dalam Serat Kalatidha, tentang datangnya zaman Kaliyuga, zaman perubahan yang merusak seluruh tatanan.
Warisan leluhur
Ronggowarsito tidak hanya menolak hegemoni pengetahuan kolonial, dia juga menolak hegemoni agama yang meminggirkan warisan leluhur. Dalam bukunya, Gatholoco (2012), pengkaji sejarah Nusantara, Damar Shashangka, menduga, Ronggowarsito adalah penulis Serat Gatholoco yang sarkastik, sekaligus penuh ungkapan sufistik yang mendalam.
Ronggowarsito-cucu pujangga besar Raden Ngabehi Yasadipura II (kakek) dan Raden Ngabehi Yasadipura II (buyut)-menurut Fay, adalah intelektual Jawa terakhir yang mengembangkan pengetahuan tentang Jawa. Setelah itu, pengembangannya diambil alih para ilmuwan didikan Belanda. Situasi tersebut memperkuat pandangan sejarawan Van Leur (1967), Indonesia lebih banyak dilihat dari geladak kapal Belanda.
Jalan yang diambil Ronggowarsito mengingatkan kepada RM Sosrokartono (1877-1952), yang memilih pulang, dalam arti fisik, psikologis, spiritual, setelah 29 tahun mengembara di Eropa. Budayawan Radhar Panca Dahana menyebutnya sebagai sosok genial, yang ingin menyatukan dua kekuatan peradaban: mistisisme Jawa dan peradaban Barat (Eropa).
Dalam hal lain, Samin Surontiko (1859-1914), pelopor Ajaran Samin, mempertahankan pengetahuan leluhur dengan menolak nalar kolonial. Nalar sama dipakai korporasi dan siapa pun yang dengan berbagai dalih berupaya menjungkirbalikkan kebenaran, termasuk dalih pengerukan sumber daya alam akan menyejahterakan rakyat.
Di makam Ronggowarsito, siang itu, kami menyelami makna "zaman edan" yang terus berlangsung di semua lini; suatu zaman yang meraibkan nurani dan mata hati....
(MARIA HARTININGSIH dan AHMAD ARIF)